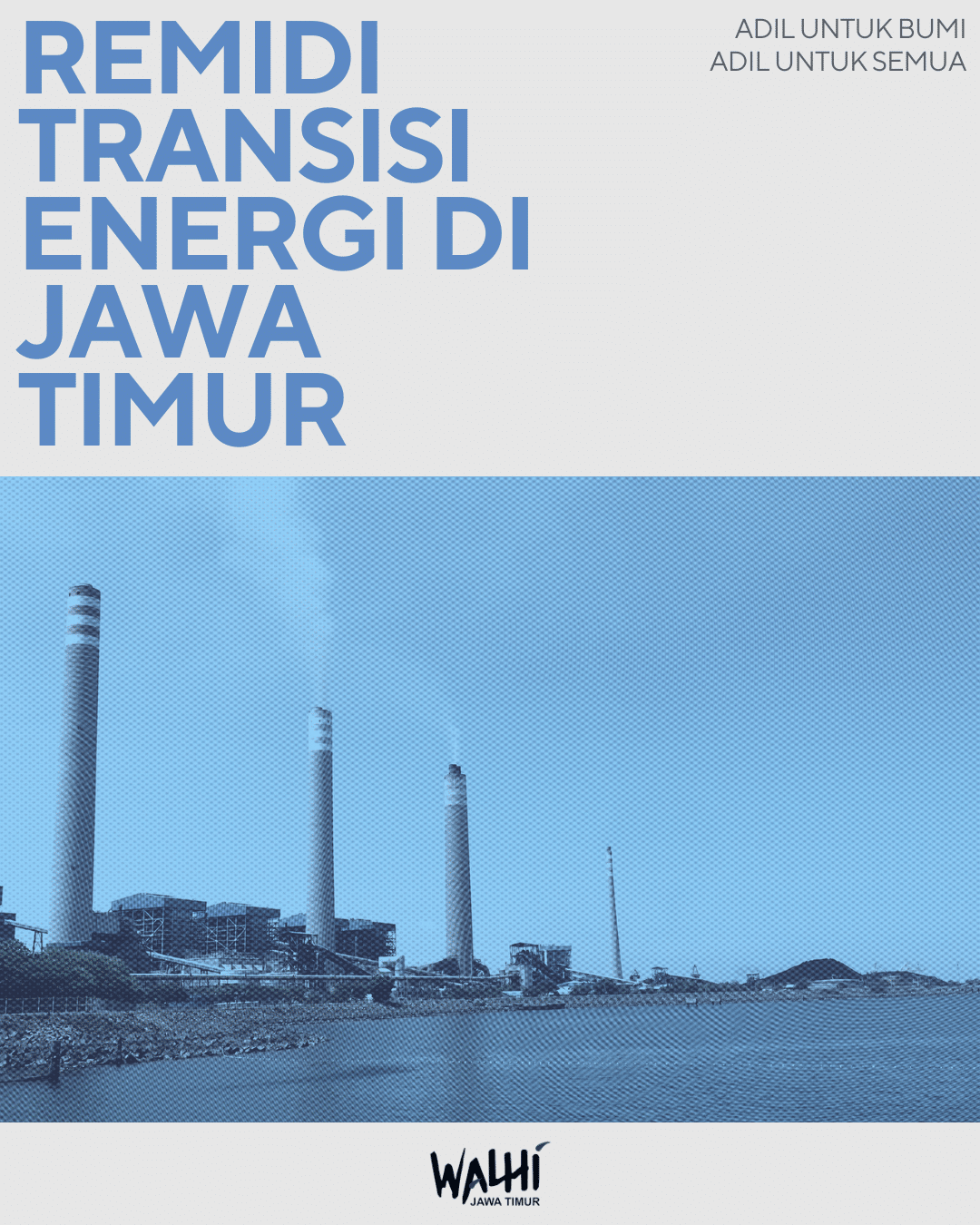Catatan ini adalah seri kampanye hari lingkungan hidup. Dengan merujuk tema adil untuk bumi, adil untuk semua. Kami mencoba menarasikan suara menjadi sebuah bacaan yang harapannya dapat menjadi bahan diskusi, serta argumentasi, mengapa kita berlu bergerak. Seri ini akan terbagi tiga, pertama terkait transisi energi di Jawa Timur, kedua terkait persoalan eksploitasi alam dan terakhir ajakan untuk bersuara
Transisi energi telah menjadi jargon wajib dalam setiap forum internasional, dari COP hingga G20. Di tengah krisis iklim dan keterbatasan energi fosil, pergantian menuju energi baru terbarukan (EBT) memang tak terelakkan.
Namun, realitas transisi energi di Jawa Timur justru memperlihatkan sebuah paradoks: dipromosikan sebagai solusi berkelanjutan, tetapi dibajak kepentingan industri dan minim partisipasi masyarakat.
Sebagai contoh, kala PLTU berusia tua masuk dalam skema pensiun, termasuk PLTU Paiton. Skema ini ditargetkan dilakukan pada tahun 2030, sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian ESDM pada Agustus 2024 silam.
Sayangnya alih-alih mendorong pemensiunan, justru yang terjadi sebaliknya. Pemerintah belum memiliki peta jalan pemensiunan, bahkan cenderung tidak punya kehendak untuk mengimplementsikan rencana tersebut.
Narasi Sesat Terbarukan
Hal ini dibuktikan dengan skema co-firing yang sedang digencarkan. Praktik tersebut dikatakan sebagai solusi untuk mengurangi emisi dan dikategorikan sebagai bentuk EBT oleh pihak pemerintah, khususnya pengelola PLTU Paiton.
Padahal praktik co-firing atau mencampurkan biomassa dengan batu bara saat produksi listrik. Praktik ini adalah contoh nyata dari greenwashing. Meski menggunakan pelet kayu atau serbuk kayu yang diklaim ramah lingkungan, kebijakan ini justru memperpanjang usia PLTU batubara yang seharusnya dipensiunkan. Co-firing hanyalah energi kotor berkedok hijau.
Begitu juga dengan proyek Refuse Derived Fuel (RDF) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Surabaya, yang secara bertahap akan direplikasikan di beberapa wilayah kabar-kabarnya Malang, Mojokerto hingga Gresik.
Rencana ini memang tampak baik dan solutif. Tetapi proyek tersebut tidak didesain untuk menyelesaikan persoalan struktural sampah seperti pola konsumsi berlebih. Karena proyek ini hanya memusnahkan sampah, bukan mengurangi. Sekaligus bentuk pelanggengan bisnis seperti biasa.
Sehingga secara praktikal proyek-proyek yang diklaim berkelanjutan tersebut, hanya mengalihkan sampah menjadi residu berbahaya dan emisi beracun yang membebani warga sekitar.
Ironisnya, proyek energi terbarukan pun tak luput dari masalah. PLTS Sumenep merampas 110 hektare lahan kebun warga dan pesantren, bahkan berlokasi di daerah krisis air yang mengancam sumber mata air vital. Proyek geothermal di pegunungan Lawu, Wilis, Arjuno, Welirang, Semeru, Argopuro, Raung, dan Ijen mengancam kawasan lindung dan berpotensi memicu bencana ekologis.
Yang lebih parah, proyek-proyek ini dilakukan tanpa konsultasi layak. Masyarakat baru tahu saat proyek dalam fase pembukaan lahan dan pra pembangunan mencuat. Tentu secara prinsip proyek-proyek tersebut melanggar prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang seharusnya menjadi syarat mutlak.
Target Muluk, Realitas Pahit
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan bauran EBT mencapai 12,15% pada 2025 dan 23,76% pada 2050. Namun capaian 2022 baru 9,36%—jauh dari target yang kian mendekat. Bauran energi masih didominasi minyak bumi (44,9%), batubara (32,4%), dan gas bumi (13,3%). Sektor industri menyerap 54% total energi, sementara ketimpangan akses listrik masih terjadi di Madura dan Jawa Timur selatan.
Kondisi ini bukanlah fenomena unik Jawa Timur. Dalam analisisnya “Towards a Just Energy Transition in Southeast Asia”, peneliti Mirza Sadaqat Huda menunjukkan pola serupa di kawasan Asia Tenggara.
Huda menekankan bahwa transisi energi yang adil membutuhkan lebih dari sekadar pergantian sumber energi—diperlukan pengakuan hak masyarakat terdampak, distribusi manfaat yang setara, dan penguatan kapasitas komunitas akar rumput.
Temuan Huda sangat relevan dengan kondisi Jawa Timur. Dia menyoroti bahwa inisiatif transisi energi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Vietnam, masih dikuasai elit ekonomi-politik yang berkepentingan besar dalam industri fosil.
Di Indonesia, 76% masyarakat bahkan tidak mengetahui keberadaan dan tujuan Just Energy Transition Partnership (JETP)—cermin nyata minimnya partisipasi dan transparansi yang juga terjadi di Jawa Timur.
Huda juga menekankan pentingnya tata kelola inklusif dan mekanisme pembiayaan yang adil. Tanpa kontrol publik dan pendanaan transparan, proyek transisi energi berisiko menjadi instrumen baru mempertahankan ketimpangan lama.
Analisis ini menguatkan dugaan bahwa transisi energi di Jawa Timur mencerminkan gejala umum—agenda yang seharusnya memperbaiki ketimpangan justru menjadi ruang kontestasi elit dan proyek korporat yang tidak menjawab kebutuhan rakyat.
Strategi dalam RUED Jatim pun terkesan deklaratif tanpa langkah tegas menghentikan dominasi energi fosil. Tidak ada pendekatan mendasar terhadap masalah ketimpangan energi, dan konservasi energi belum menjadi budaya luas.
Agenda Koreksi Mendesak
Transisi energi di Jawa Timur harus dikoreksi agar tidak menjadi ajang greenwashing dan bagi-bagi kue kelompok elit serta korporat.
Lima prinsip mendasar perlu ditegakkan yaitu: 1). Pensiun dini energi fosil secara nyata dengan menutup PLTU batubara bertahap dan menghentikan co-firing; 2). Partisipasi publik dan FPIC dalam semua proyek energi; penguatan energi komunitas skala kecil dengan model “satu desa satu sumber energi”; 3). Integrasi dengan keadilan sosial-ekologis tanpa menggusur lahan produktif; 4). Reformasi tata kelola energi yang demokratis berbasis hak, bukan pasar semata.
Di sini kami juga menekankan pentingnya Forum Transisi Energi Daerah yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, komunitas lokal, dan pemerintah. Ruang tersebut diharapkan menjembatani keterbukaan dan partisipasi, serta penting sebagai ruang bersama untuk merumuskan arah transisi yang benar-benar inklusif.
Karena itu, kami WALHI Jawa Timur akan terus bersuara menuntut transisi energi yang memihak rakyat, bukan modal.
WALHI Jawa Timur memandang bahwa transisi energi di Jawa Timur berpeluang membangun masa depan yang bersih, adil, dan berkelanjutan. Namun tanpa koreksi arah dan kritik tajam, transisi ini justru akan melanggengkan ketidakadilan lama dalam kemasan baru.
Energi adalah hak asasi, bukan komoditas. Transisi energi bukan semata urusan teknologi, tetapi soal keadilan dan masa depan bumi bersama.